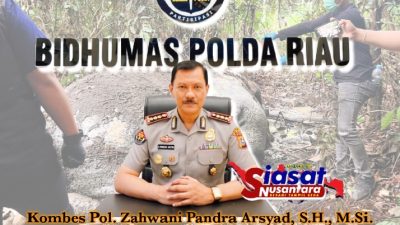Bangka Belitung, siasatnusantara.com— Di ruang rapat yang dinginnya menusuk lebih tajam dari angin laut Belo Laut di musim angin selatan, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali memanggil enam perusahaan sawit yang telah lama menguasai hamparan pulau ini. Senin (24/11/2025).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama APDESI dan ABPEDNAS Bangka Barat digelar, menyisakan satu pertanyaan yang menggantung seperti kabut di atas hutan kelapa: Di mana dan bagaimana keadilan plasma untuk rakyat?
Pertemuan itu menghadirkan 25 desa sebuah jumlah yang cukup untuk melambangkan keresahan berjamaah. Mereka datang bukan membawa amarah yang meledak-ledak, tetapi getir yang matang.
Seperti pepatah Melayu Bangka: “Air tenang jangan disangka tak beriak; tapi kalau terlalu lama diam, bisa berubah jadi payau.”
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, membuka rapat dengan kalimat yang terdengar seperti pengakuan atas luka lama.
“Berdasarkan informasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat 30.000 hektare Hak Guna Usaha (HGU) yang kini dikelola enam perusahaan sawit besar,” ujarnya.
Dengan aturan yang berlaku terutama Permentan 98/2013, 20 persen lahan seharusnya dialokasikan sebagai plasma untuk masyarakat. Artinya, sekitar 7.000 hektare wajib diberikan.
Namun kenyataannya?
“Yang baru terealisasi hanya 1.311 hektare, atau sekitar 5,4 persen. Sangat jauh dari kewajiban,” tegas Didit, suaranya berat, seperti menahan kenyataan yang enggan disebutkan.
Plasma seharusnya menjadi jalan agar Desa-Desa di Bangka Barat tidak sekadar menjadi penonton dari hamparan sawit yang mereka lihat setiap hari. Namun Didit mengingatkan, plasma itu wajib berada di luar HGU. Bila desa tidak punya lahan, perusahaan dapat melakukan mekanisme Nilai Obyek Pengganti (NOP) yang dinilai oleh tim independen.
“Prinsipnya kewajiban ini mutlak. Ada sanksi jika tidak dilaksanakan,” katanya.
Ucapan itu terdengar seperti petikan pantun lama: “Janji di bibir jangan sampai jadi buih; hilang ditiup angin sebelum menyentuh pantai.”
Namun begitulah yang terjadi bertahun-tahun, janji yang mengering sebelum menyentuh tanah.
Para anggota DPRD daerah pemilihan Bangka Barat sepakat mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja). Tujuannya menyelesaikan persoalan plasma dan CSR yang selama ini berputar-putar seperti tarian rudat tanpa akhir.
“Usulan ini akan kami bawa ke Badan Musyawarah. Harapan kami bisa disetujui,” kata Didit.
Namun masyarakat desa yang hadir tampak tidak sepenuhnya hanyut oleh kata “harapan”. Sebab sudah terlalu sering mereka mendengar harapan tanpa perubahan. Bagi mereka, Panja bukan jawaban bila tak dibarengi tindakan.
Sembari menunggu keputusan Panja, Didit menegaskan agar perusahaan sawit segera melakukan koreksi dan berkoordinasi dengan desa. Kewajiban plasma dan CSR tidak boleh lagi menjadi wacana yang digantung di dahan terendah hutan kelekak mudah terlihat, tetapi tak pernah bisa dicapai.
Perusahaan dituntut menjalankan Permentan 98/2013 dan Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012. Setidaknya, itu pesan resmi. Namun di balik pesan resmi itu, terasa gema satirenya.
Bagaimana mungkin pulau yang kecil ini sanggup menampung lebih banyak janji daripada kenyataan?
Di Bangka Barat, lahan bukan sekadar tanah. Ia adalah sumber identitas, nafkah, dan sejarah. Di sinilah satire keadilan menemukan bentuknya:
Perusahaan menguasai ribuan hektare, sementara desa-desa masih menunggu hak yang bahkan tak sampai seperenam dari kewajiban.
Seorang Kepala Desa berbisik setelah rapat.
“Kami ini macam berdiri di tepi dusun, melihat ladang kami berubah, tapi tengok hasilnya tak pernah sampai ke dapur,” ucapnya.
Kalimat itu lebih jujur daripada lembaran risalah rapat manapun.
RDP ini bukan sekadar forum. Ia adalah cermin retak persoalan struktural:
– Ketimpangan penguasaan lahan
– Rendahnya realisasi plasma
– CSR yang kabur tanpa laporan transparan
– Ketiadaan pengawasan yang kuat
Di atas meja rapat, semua terdengar tertata.
Di lapangan? Yang tertata hanya barisan pohon sawit ratusan kilometer, rapi, teratur, tanpa hati.
(*/Belva).